1.Geographia,Ptolemy
Why it changed the world: It set practical standards in geography which lasted 1500 years, and is our best record of the state of geographic knowledge in the 2nd century.
Claudius Ptolomeus adalah seorang ahli geografi yang semula sering berada di pelabuhan kota-kota Yunani untuk mendengarkan cerita pelaut-pelaut yang baru kembali dari pelayaran. Ptolemeus tidak puas hanya mendengar laporan pelaut di kota-kota pelabuhan Yunani. Ptolomeus ingin sekali memperoleh cerita-cerita dari pelaut Arab yang kabarnya berlayar sampai ke negeri yang jauh di bawah angin, atau khatulistiwa. Maka ia mencari tempat tinggal baru di Iskandariah, Mesir. Laporan tentang Iobadiou itu didengarnya dari pelaut Arab.
Pada tahun 160, seorang ahh geografi Yunani bernama Claudius Ptolomeus menulis sebuah buku bernama Geographia. Dalam buku itu disebutkan bahwa Iabadiou adalah sebuah negeri yang subur, menghasilkan banyak emas, dan mempunyai bandar niaga bernama Argyre yang tempatnya di ujung barat negeri itu. lobadiou adalah Jawa. Sedangkan Argyre adalah bahasa Yunani yang berarti perak.

2.The Canterbury Tales,Geoffrey Chaucer
Why it changed the world: Popularized the use of vernacular English as the dominant language in English literature (rather than Latin or French commonly used at the time) - the Canterbury Tales set the standard for future works of English literature.
Bagi Anda yang pernah mempelajari karya-karya sastra Inggris Periode Abad Pertengahan (1150-1400) pasti mengenal seorang sastrawan terkenal Inggris, Geoffrey Chaucer (1340 – 1400). Chaucer boleh dibilang penyair terbesar abad pertengahan. Akhir abad pertengahan adalah milik Chaucer atau sering disebut The Age of Chaucer (Zaman Chaucer). Chaucer tergolong orang yang serba bisa. Ia seorang penguasaha, pejabat pemerintah, perantau, prajurit, ilmuwan, penyair dan lain–lain. Karya terbesar Chaucer adalah The Canterbury Tales. Karya ini mengisahkan sebuah ziarah imajiner para biarawan pada 11 April, 1387 menuju Katedral Canterbury untuk mengunjungi pusara Santo Thomas A. Beckett. Karya ini merupakan suatu kumpulan 70 sajak naratif, dengan panjang baris dan pokok masalah yang beraneka ragam. The Canterbury Tales memberikan gambaran realistik seputar kehidupan masyarakat Inggris. Kumpulan sajak ini kaya akan humor meskipun terdapat kritik yang ditujukan pada berbagai tokoh, khususnya para pendeta yang melalaikan tugas-tugasnya dan yang masih mementingkan kesenangan duniawi. Tak pelak, karya ini menyajikan deskripsi sosial kehidupan para pendeta, biarawan-biarawati atau tokoh agama yang korup, serakah dan penipu, alih-alih sebagai model role bagi masyarakat Inggris yang banyak didera oleh kemiskinan di masa itu.
Banyak tokoh dalam The Canterbury Tales ini merepresentasikan prilaku dan tabiat yang berseberangan dengan apa yang secara tradisional diharapkan dari mereka. Hal ini lantaran Gereja Katolik—yang menguasai Inggris, Irlandia dan sebagian besar Eropa pada abad ke-14—luar biasa kaya. Katedral-katedral mewah dibangun nyaris di setiap bandar-bandar besar di tengah-tengah penduduk yang menderita kepapaan, penyakit dan kelaparan. Fenomena kontras antara kekayaan gereja dan kemiskinan masyarakat kentara sekali, ditemukan di mana-mana. Karenanya, tokoh-tokoh dalam The Canterbury Tales ini digambarkan dengan sifat-sifat yang tamak dan penipu. Dua di antaranya adalah the Summoner (petugas pengadilan) dalam The Friar’s Tale (Kisah Rahib) dan Death dalam The Pardoner’s Tale (Kisah Sang Pengampun). The Summoner adalah seorang pegawai gereja yang menggiring orang-orang dengan tuduhan melanggar tata aturan gereja menuju sebuah pengadilan khusus yang dibentuk gereja. Tokoh ini dalam The Friar’s Tale berwatak penipu dan serakah yang kerap menyalahgunakan kedudukannya sebagai pegawai gereja yang memeras orang-orang tak bersalah demi segepok uang. Ia memiliki jaringan mata-mata rahasia yang selalu memberi laporan padanya. Atas dasar ini, ia mengeluarkan surat perintah palsu dan memeras uang dari siapapun. Alih-alih menegakkan keadilan, tindaknnya justru mencerminkan kazaliman. Chaucer menulis cerita ini sebagai kritikan terhadap kehidupan para pendeta dan biarawan gereja yang diselubungi ketamakan dan mentalitas korup sepanjang Abad Pertengahan.
Sementara, dalam The Pardoner’s Tale, segenap tokohnya berupaya mencari Death (kematian). The Pardoner menyifati Death in layaknya manusia, manusia yang jahat. Sepanjang abad ke-14 kematian sesuatu yang lumrah terjadi. Wabah penyakit dinilai sebagai pembunuh terbesar orang-orang di saat itu. Tak seorang pun yang tahu apa penyebabnya, sehingga hal ini dianggap misterius atau dicap sebagai peristiwa ganas. Dalam kisah ini, kematian mengalami personifikasi; menjadi nama seorang tokoh. Siapapun dalam kisah tersebut yang mencarinya—sang tokoh yang bernama ‘kematian’ (Death)—bakal menghadapi dua nasib yang sama-sama malang; mati atau terbunuh satu sama lain ketika mendekati si kematian ini. Esensi yang hendak diketengahkan oleh Chaucer lewat kata-kata the Pardoner ini adalah bahwa sifat-sifat bejat, semisal kekikiran, ketamakan dan korupsi bakal membawa pada kematian. Tentu the Pardoner sendiri adalah seorang “dasa muka” (baca: munafik) dan menggenapi seluruh sifat-sifat jahat berkenaan. Pada akhir cerita, ia mencoba menjual semua barang-barang peninggalan gereja demi mendapatkan uang. Nyatanya selaku seorang gerejawan, ia setali tiga uang dengan the Summoner dalam The Friar’s Tale.
Kedua-dua karakter tersebut di atas—The Summoner dan Death—mewujud sebagai tamsil pejabat-pejabat gereja yang “memperkosa” peran yang seyogianya mereka lakoni. Jangankan tampil sebagai pemimpin-pemimpin agama yang berlaku jujur dan adil, mereka malah bersikap layaknya para pendusta munafik yang mereka hujat dalam khotbah-khotbah yang mereka ujarkan. Sekali lagi, penulis—Chaucer—ingin menunjukkan betapa Gereja Katolik telah bermetamorfosis sebagai institusi keagamaan yang bakhil dan korup. Poinnya tetap tak berubah, bahwa “radix malorum est cupiditas”(ketamakan adalah akar dari segala kejahatan).
Demikianlah ironinya kehidupan para biarawan yang semestinya menjadi panutan publik. Kehidupan para biarawan tidak meneladankan kesederhanaan, malah menikmati kehidupan material. Mereka rata-rata berbadan gemuk karena selalu makan enak. Mereka mengenakan pakaian yang mentereng; jubah dengan bulu mahal lengkap dengan dekorasinya. Belum lagi kebiasaan mereka yang acap berburu binatang ketimbang belajar kitab suci. Mereka berlaku lembut pada kuda-kudanya maupun anjing-anjing untuk berburu. Mereka berteman dengan para pemburu. Parahnya para biarawan ini masih punya nyali mengkhotbahkan bahwa kegiatan berburu dinilai tidak suci (unholy). Mereka menggunakan dana gereja buat kepentingan pribadi; membangun rumah yang besar dan kandang kuda serta membeli pakaian-pakaian mewah maupun perhiasan yang mahal.
Gaya hidup kalangan biarawan ini dengan telanjang menyembah sikap ingin memuaskan diri sendiri (self-indulgence). Mereka membuang ajaran-ajaran lama dan kaku lantaran tergiur dengan bujukan dunia bendawi. Secara ekstrem, mereka sepenuhnya mengabaikan ajaran-ajaran guru mereka, di antaranya Santo Benet dan Santo Maur.
Pada hemat Chaucer, kebejatan akhlak yang dipertontonkan oleh kalangan dalam gereja ini telah menodai janji doktrinal yang harus mereka patuhi sebagai para pemuka agama. Sungguhpun Chaucer tidak secara langsung menyatakannya, tapi secara gampang hal ini bisa terbaca dalam karya tersebut.
Biarawan dan biarawati seharusnya hidup dalam kesederhanaan dan tak punya hasrat kepada harta duniawi. Namun, para biarawan bergiat memiliki dan sibuk mengurus anjing-anjing kecil yang sebenarnya terlarang di lingkungan gereja. Dengan memelihara anjing, mereka telah melanggar aturan gereja yang dikenal sebagai “vow of poverty” (janji kepapaan). Namun hal yang paling mencolok adalah tatkala kalangan biarawan ini mempunyai broach yang terbuat dari emas. Kepemilikan benda ini menjustifikasi bahwa hakikatnya mereka mewakili kehidupan kalangan atas. Maka, sulit dipungkiri betapa hal ini mendorong pembaca percaya bahwa para biarawan ini memang tidak lagi mendarmabaktikan hidup dan kebaktiannya pada gereja.
Akan halnya dengan biarawati, Chaucer menghabiskan banyak waktu untuk menerangkan betapa kuatnya obsesi mereka pada etika seksual, yang ternyata memberikan kesan bahwa para biawawati lebih cocok menjadi para wanita yang dicintai dibandingkan menjadi biarawati. Pada zaman Chaucer, wanita menggunakan cara cara-cara tertentu untuk memikat dan memelihara kekasih mereka. Ini mengindikasikan bahwa para biarawati sama sekali tidak komit pada “vow of chastity” (janji kesuciaan) yang menjadi pakaian spiritual mereka. Mereka tampaknya juga wanita-wanita yang punya hasrat seksual dengan laki-laki manapun (women of promiscuity).
Lebih lanjut, para biarawati tersebut makin menabrak aturan-aturan gereja lainnya, yakni “vow of obedience” (janji ketaatan). Sudah menjadi keniscayaan bahwa seorang biarawati adalah pelayan Tuhan yang harus berdoa, belajar, berbakti pada-Nya dan menjalani hidup yang terbatas serta bebas dari godaan. Kenyataannya, bukan saja mereka telah menabrak janji-janji lainnya tapi mereka juga tidak berdoa pada Tuhan setiap hari. Mereka tidak bertindak di atas aturan Tuhan lantaran mereka bekerja lebih sebagai individual daripada selaku para pelayan Tuhan. Oleh karena itu, Chaucer akhirnya hendak berwasiat kepada pembaca bahwa kita seharusnya tidak boleh menilai seseorang lewat penampilan luarnya saja. Perbedaan dalam karakter luar para peziarah dalam kisah The Canterbury Tales ini seringkali berbeda dibandingkan kepribadian yang tampak sepanjang kisah ini.

3.Lady Chatterley’s Lover,D H Lawrence
Why it changed the world: It brought the concept of book censorship to a head and eventually helped to overturn it.
Lady Chatterley� Lover adalah roman sastra terkenal yang kini telah menjadi karya klasik dalam khazanah sastra dunia. Novel karya penulis Inggris D.H. Lawrence ini terbit pertama kalinya pada tahun 1928. Sadar bahwa novelnya tak mungkin diterbitkan di Inggris, maka Lawrence menerbitkannya sendiri di Florence, Italia. Novel ini menuai kontroversi karena deskripisi persetubuhan antara dua orang yang berbeda strata sosial begitu kentara dan bertaburan disepanjang novelnya. Hal yang saat itu masih dianggap tabu untuk diungkap secara eksplisit dalam sebuah karya sastra.
Beberapa pedagang buku di Inggris menolak novel ini dijual di toko-toko mereka. Sementara itu buku yang dikirimkan kepada para pemesan di AS sering disita oleh pihak otoritas bea cukai. Bahkan Presiden Eisenhower menganggapnya sebagai bacaan �dreadful�.
Berbagai pelarangan justru semakin membuat novel ini laris manis. Di Eropa sendiri novel itu laku keras. Namun karena novel ini dianggap sebagai bacaan tidak senonoh dan sesuai dengan UU yang berlaku saat itu bahwa buku-buku yang dianggap tidak senonoh tidak akan dilindungi oleh UU hak cipta internasional, maka para pembajak dengan bebas mencuri teks novel ini dan mencetak ulang dengan harga yang lebih murah. Untuk melawan para pembajak Lawrence terpaksa menerbitkan edisi murah dalam bahasa Perancis.
Lawrence juga pernah ditawari oleh penerbit Inggris untuk membuat edisi baru dengan menghilangkan bagian-bagian yang menurut mereka tidak pantas. Untuk itu Lawrence ditawari imbalan yang besar. Tentu saja Lawrence menolaknya karena menurutnya dengan menghilangkan bagian-bagian yang dianggap tidak pantas malah akan membuat karyanya hancur.
Penerbit buku bergengsi di London, Penguin Books Limited, akhirnya menerbitkan novel itu secara utuh pada tahun 1960. Karena itu, penerbit tersebut diadili di Pengadilan Old Bailey, London. Sejumlah saksi memberikan pandangan yang mendukung novel ini. Akhirnya pengadilan secara resmi menilai dan memutuskan bahwa The Lady Chaterley�s bukanlah karya pornografis. Penguin pun memenangi perkara dan buku tersebut secara utuh boleh beredar di Inggris. Semenjak itu novel ini dapat didistribusikan dan diterbitkan dengan bebas di berbagai negara tanpa khawatir dicap sebagai bacaan porno. Dan kini Berbagai kajian sastrawi dilakukan terhadap novel yang menarik perhatian pembaca popular dan juga mahasiswa sastra di berbagai belahan dunia.
Novel ini sendiri mengisahkan kisah cinta terlarang antara Connie dengan Olivers Mellors. Lady Chatterley adalah gelar yang diberikan pada Connie setelah ia menikah Cliiford Chatterley. Connie sendiri berasal dari keluarga kaya yang dibesarkan dalam pendidikan dan pergaulan modern keluarga Inggris pada saat itu. Sedangkan Clifford lahir dari keluarga bangsawan pemilik tambang batu bara di Travershall � Inggris. Ia mengenyam pendidikan tinggi hingga ke Cambridge dan berdinas sebagai tentara saat PD I meletus. Malang nya setelah perang usai Clifford harus pulang dalam keadaan lumpuh. Dan mulailah Clifford menjalani hari-harinya bersama Connie di rumah besarnya di Wragby di sebagai seorang penulis.
Pasca kelumpuhannya Cliford menjadi pribadi yang terluka. Ia harus terus berada diatas kursi roda mekanis yang bisa bergerak sendiri dengan menekan tombol-tombolnya. Clifford senantiasa sendirian. Ia seperti orang yang tersesat. Ia butuh Connie disampingnya untuk meyakinkan kalau dia tetap ada. Walau mereka selalu berdekatan, tubuh mereka menjadi asing satu sama lain. Mereka begitu intim, namun sama sekali tidak pernah bersentuhan. Connie merasa ia tak mendapatkan kehangatan dari suaminya.
Setelah dua tahun di Wragby dan menjalani hidup pengabdian pada suaminya, Connie merasa hidupnya bersama Clifford tidaklah bahagia. Walau hidup berkecukupan dan menikah dengan seorang bangsawan, ia tetap tidak bahagia dan merasa belum mendapat pemenuhan dalam hidup. Connie tahu bahwa dirinya akan hancur. Ia telah kehilangan dunia dan vitalitas masa mudanya yang pernah dia nikmati sebelum dia menikah.
Keterasingan, kesepian, bosan, hampa, dan perasaan tertindas oleh sikap patriakhi suaminya membuat dirinya tak bergairah dan mengalami kegelisahan yang semakin hari semakin memuncak. Ketika gelisah datang, ia berlari melintasi taman dan meninggalkan Clifford. Lari dari semua orang menuju hutan, tempat ia bisa melupakan semua kegelisahannya.
Dalam hutan itulah Connie bertemu dengan Oliver Mellors si penjaga hutan yang merupakan pegawai Clifford. Berawal dari ketika Connie ditugasi oleh Clifford untuk mengirimkan pesan pada Mellors akhirnya mereka kerap bertemu. Walau awalnya keduanya tak saling suka namun perasaan kesepian yang sama-sama mereka alami membuat mereka lambat laun saling mencintai dan membutuhkan. Bersama si penjaga hutan itulah akhirnya Connie menemukan kehangatan dan keteduhan batinnya.
Connie terperangkah di antara dua pria. Pada Clifford ia tetap melaksanakan kewajibannya sebagai istri, namun ia juga tetap menjalin hubungan cintanya dengan Mellors di hutan. Hubungan mereka berlanjut dengan aktifitas seks di pondok di tengah hutan di tempat kediaman Mellors hingga akhirnya Connie hamil. Bisa dibayangkan bagaimana sikap Clifford jika kelak mengetahui bahwa dirinya hamil karena perselingkuhannya dengan lelaki kelas bawah yang notabene pegawainya sendiri. Namun Connie tidak takut, ia memang menghendaki anak dan kehamilannya ini dijadikannya alasan bagi dirinya untuk meminta cerai dari Clifford. Clifford terguncang, namun ia menampik keinginan istrinya untuk bercerai dan menawarkan sebuah solusi yang dianggapnya terbaik.
Ada banyak hal yang menarik dari novel ini. Seperti yang menjadi kontroversi sejak novel ini diterbitkan, novel ini memang memiliki banyak deksrpisi erotis. Walau D.H. Lawrence membungkusnya dalam balutan kalimat-kalimat sastrawi namun tetap saja pembaca akan terbakar oleh deskripsi persetubuhan Connie dan Mellors. Namun tentunya bukan maksud penulisnya hanya untuk sekedar menghadirkan kisah erotis tanpa makna.
Persetubuhan antara Connie dan Mellors bukan hanya sekedar pemuasan nafsu mereka semata, tetapi sebagai perwujudan kelegaan atas pribadi-pribadi yang terkukung. Hubungan seks diantara mereka melahirkan ketenangan sejati bagi Connie. Jadi tujuan seks dalam novel ini lebih pada penyembuhan dan bukan sekedar pemuasan nafsu. Walau seks yang mereka lakukan adalah hal yang terlarang namun seks membawa kelahiran kembali Connie dan Mellors untuk bisa membuka diri dan menapak kehidupan baru mereka.
Karakter-karakter yang dihidupkan oleh D.H. Lawrence dalam novel ini sangatlah menarik. Walau merupakan roman percintaan namun novel ini bukanlah novel yang mendayu-dayu dan cengeng. Hampir semua tokoh dalam novel ini mentransformasikan dirinya dari pribadi yang rapuh menjadi pribadi yang kuat dan melawan. Clifford, Connie, dan Mellors awalnya merupakan pribadi-pribadi yang tertutup, tersisih, dan kesepian, namun berbagai peristiwa telah merubahnya menjadi pribadi yang kuat dan penuh perlawanan. Contohnya adalah perlawanan terhadap tradisi dan pendobrakan sekat-sekat kelas yang dilakukan secara simbolis oleh perselingkuhan Connie danMellors.
Selain itu melalui novel ini kita juga dapat menangkap kritik sosial terhadap muramnya kehidupan di Inggris setelah perang di tahun 1920-an. Masyarakat terjebak ke dalam lapisan-lapisan kelas, industrialisasi mulai merasuk, dan uang menjadi senjata ampuh untuk pencapaian kekuasaan. Melalui tokoh Clifford, seorang berdarah biru dan tuan tanah pemilik tambang akan terungkap bagaimana sikap para bangsawan terhadap para pekerja tambang yang bagi mereka bukan lagi manusia seutuhnya melainkan hanya sekedar alat produksi untuk mengeruk keuntungan bagi usaha mereka.
Jadi novel ini bukanlah sekedar novel erotis semata seperti yang mungkin selama ini menjadi pendapat umum atas karya terkenal D.H. Lawrence ini . Ada banyak hal yang bisa dimaknai dalam kisah cinta Lady Chaterly. Michael Squares, editor Penguin Books menulis dalam kata pengantarnya bahwa Lawrence berusaha membangunkan dan mengarahkan rasa simpati para pembaca tanpa membuat novel ini menjadi sebuah kebosanan.
Salah satu yang ingin disampaikan oleh Lawrence dalam novel ini adalah upaya menyadarkan masyarakat atas dirinya sendiri, mempertanyakan berbagai asumsi yang telah mengakar dan membangkitkan sebuah kejujuran dan keberanian yang menantang. Karena itulah tampaknya karya yang telah berusia lebih dari 75 tahun ini masih relevan untuk terus dibaca dan dimaknai.
Bersyukur kini karya klasik ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dibanding edisi aslinya, novel terjemahannya ini tampak lebih gemuk karena penerbit memasukkan berbagai artikel tambahan baik di awal maupun akhir novel ini. Di bagian awal, pembaca akan disuguhkan dengan 4 buah artikel berupa Catatan untuk edisi Penguin, Kata Pengantar, dan Catatan Panjang dari Penulis yang menghabisi sekitar seratus halaman sebelum kita masuk dalam novelnya sendiri. Sedangkan di akhir novel masih ada tambahan berupa Riwayat Panjang D.H. Lawrence, dan Apendiks sebanyak 23 halaman.
Bagi para pemerhati sastra, artikel-artikel tambahan itu tentunya sangat bermanfaat, namun bagi pembaca awam mungkin menjadi tak terlalu bermanfat karena membaca artikel-artikel tersebut ternyata cukup melelahkan. Novel ini dicetak diatas kertas yang bagus sehingga terkesan mewah, nyaman dibaca, dan layak dikoleksi, namun konsekuensinya harga buku ini menjadi relatif mahal yang tentunya membuat calon pembeli berpikir ulang untuk membeli novel seharga 99 ribu ini.
Beberapa kesalahan cetak juga ditemui di novel ini. Dari segi terjemahan bisa dibilang baik, walau ada beberapa frasa yang saya anggap janggal namun tak sampai mengurangi kenikmatan saya membaca novel ini. Ada satu hal yang tidak konsisten dalam terjemahannya. Di cover belakang novel ini disebutkan Connie berselingkuh dengan penjaga kebun/tukang kebun, sementara di seluruh bagian novel ini, profesi Oliver Mellors tidak disebut sebagai tukang kebun melainkan penjaga hutan.

4.The Republic,Plato
Why it changed the world: Plato’s contrast between the imperfect world of mortals and the perfect forms of immortal souls had a great deal of influence over Christianity and Islam and Western philosophy in general.
Salah satu karya monumental Plato adalah The Republic, yang dalam bahasa Yunani artinya “sistem politik.” Karya ini ditulis kira-kira pada 380 SM, dan dipandang sebagai salah satu karya filsafat dan teori politik yang paling berpengaruh. Ini juga merupakan karya Plato yang paling terkenal.
Plato menghasilkan sejumlah karya, yang berkaitan dengan filsafat politik, seperti Republic, Statesman, dan Laws. Namun, Republic adalah pusat dari filsafat politik Plato. Karena, karya-karya Plato yang lain --seperti Apology, Charmides, Crito, Euthydemus, Gorgias, Protagoras, dan Menexenus—bisa dipahami dengan melihat hubungannya pada teks utama di Republic.
Makalah ini mencoba mengangkat sejumlah pemikiran Plato di bidang politik. Untuk menyederhanakan dan memudahkan pembahasan, pemikiran Plato yang diulas di sini dibatasi pada topik-topik tertentu. Pemikiran Plato itu akan dianalisis dengan membandingkannya pada pemikiran tokoh-tokoh lain, serta coba ditempatkan dalam konteks masa kini.
Dalam membahas pemikiran Plato, penulis menggunakan pendekatan filsafat politik. Filsafat politk pada hakikatnya menuntut agar segala klaim (legitimate authority) atas hak untuk menata masyaraksat (yang dimiliki oleh Pemerintah Negara) dapat dipertanggungjawabkan di hadapan akal dan hati kemanusiaan. Pertanggungjawaban publik (accountability) mrerupakan perwujudan dari tanggung jawab rasional atas kekuasaan.
Legitimasi politik di sini tidak selalu sama dengan legitimasi moral (etis-filosofis). Legitimasi politik dapat dipahami sebagai legitimasi sosial (sosiologis) yang telah mengalami proses artikulatif dalam institusi-institusi politik yang representatif. Sedangkan legitimasi moral (etis) mempersoalkan keabsahan wewenang kekuasaan politik dari segi norma-normal moral, bukan dari segi kekuatan politik riil yang ada, dan bukan pula atas dasar ketentuan hukum (legalitas) tertentu.

5.On Liberty,John Stewart Mill
Why it changed the world: Most of Mill’s theories are now full integrated into modern democracies - particularly the need to protect the rights of the individual.

6.The Histories,Herodotus
Why it changed the world: They are the source of much of our knowledge of the ancient world and the foundation of history in Western literature.

7.Canon Of Medicine,Avicenna
Why it changed the world: It brought together the knowledge and theories of Ancient Greek, Persian, and Indian medicine (largely forgotten otherwise) and combined it with contemporary 11th century understanding. It laid the foundations of modern medical science.

8.The Interpretation Of Dreams,Sigmund Freud
Why it changed the world: While many of Freud’s theories have now been dismissed by modern specialists, his concept that the unconscious retains much that the conscious mind appears to have forgotten has changed and influenced the way that people think about themselves.

9.The Analects,Confucius
Why it changed the world: A truly radical text in its time, the Analects have been the dominant influence on Chinese thought and culture.

10.Principia Mathematica,Isaac Newton
Why it changed the world: Newton’s Principia, published in 1687, laid the foundation for much of modern physics and mathematics.

sumber : http://bughisy-anda.blogspot.com/2009/03/top-10-buku-buku-yg-mampu-mengubah.html
faizal muttaqin
skip to main |
skip to sidebar
Translate
pengunjung
You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "
Top Navigation
Follower
About Me
Archive
- Juni 2011 (3)
- Mei 2011 (207)
- April 2011 (53)
- Maret 2011 (30)
- Februari 2011 (15)
- Januari 2011 (17)
- Desember 2010 (10)
- November 2010 (4)
Design by Web2feel.com | Bloggerized by Lasantha - Premiumbloggertemplates.com
Copyright 2010 © faizal blog's
Copyright 2010 © faizal blog's








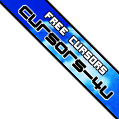
0 komentar:
Posting Komentar